Aku suka pukul dua pagi. Itu waktu yang paling aku suka di tiap belahan bumi. Pada pukul itu, tidak ada siapa-siapa kecuali aku. Tidak ada suara amuk bapak atau suara rintihan dari ibu yang kesakitan. Tidak ada debt collector yang mengetuk pintu, karena selain dosa, bapak juga suka mengumpulkan hutang. Kadang aku berpikir, apa yang sebenarnya Tuhan pikirkan ketika Dia menciptakan pukul 2 pagi?
“Alina, ini udah pukul 2 pagi,” katanya sambil memijat pundakku.
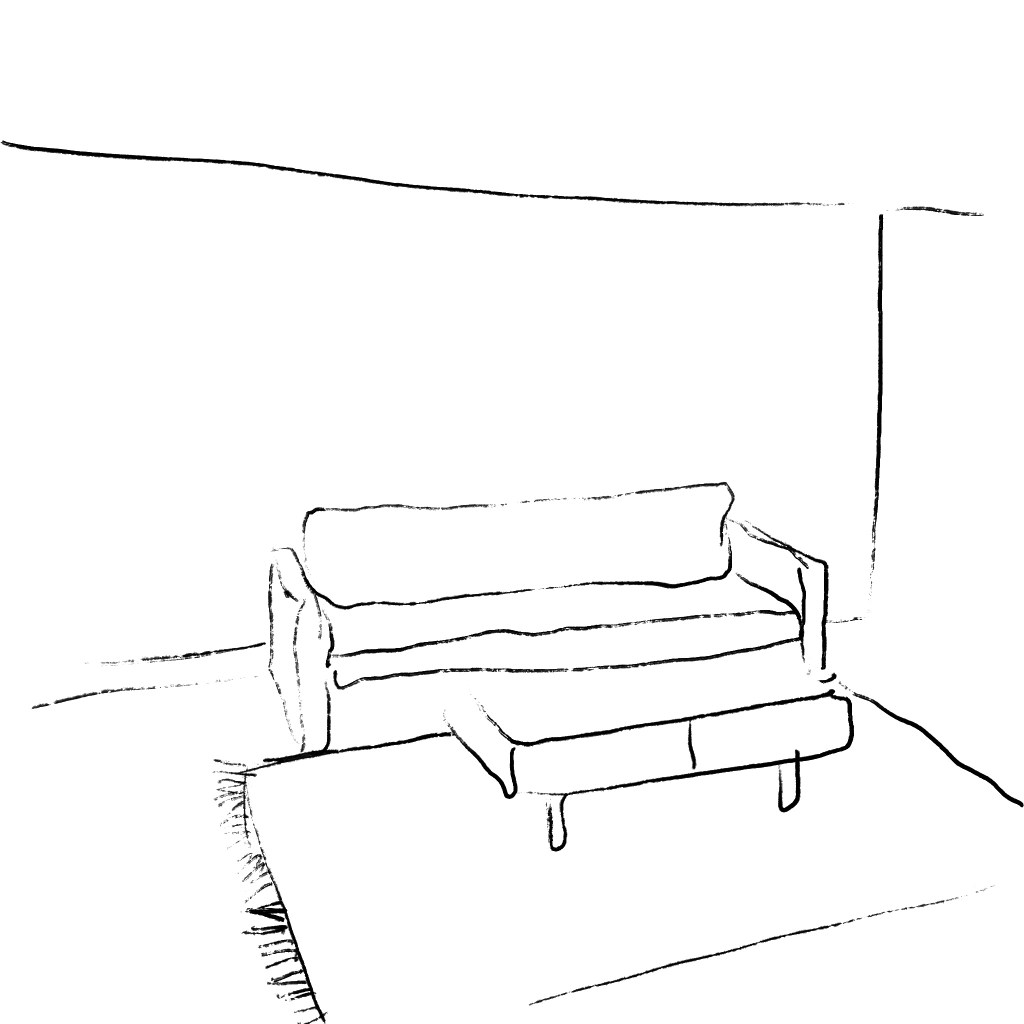
“Aku gak mau pulang,” kataku yang sudah berulang kali mengucapkan kalimat yang sama.
“Terus maunya apa?” tanyanya.
Aku maunya dia pergi, tapi tidak bisa, karena ini tempatnya dan aku tidak punya tempat lain untuk kabur. Yah, meski tidak bisa disebut kabur, karena di rumah masih ada ibu, jadi aku masih harus pulang.
“Aku mau ngobrol, apa aja yang penting bukan tentang aku.”
Ia memberiku senyum, mengambil sebatang rokok dari atas meja kemudian menyalakannya.
“Ngobrol apa, ya, kalau buka tentang kamu? Bingung, karena sekarang hidupku isinya kamu doang, Na,” katanya sambil mengisap rokoknya.
“Keren. Kita udah setahun, tapi gombalanmu seperti gak kenal usia,”
Dia tertawa. “Kamu pikir barusan aku gombal? Itu informasi, lagi.”
Aku menggeleng. “Ngawur.”
“Yaa kita emang lumayan ngawur sih, Na. Kamu pernah bayangin gak kalau kita bisa sampe selama ini? Setahun tuh… gak bentar, loh,”
“Iya. Thanks to Siti, sih. Kalau waktu itu dia gak maksa aku ikut ke Blok M, mungkin sekarang kamu pacarannya sama dia, bukan sama aku.”
“Ada gilanya juga, lo.”
“Lah bener, kan, Yo? Semua orang suka Siti. Cantik, seksi, pinter, supel. Mau dari pejabat sampe tukang sate kalau ngobrol sama dia juga pasti seneng. Dia tuh… sempurna, kurangnya cuma jatuh cinta sama laki orang aja. Yah, Tuhan emang adil ya, Yo?”
“Na, itu mah bukan kurangnya Siti. Sejak kapan jatuh cinta sama punya orang tuh sebuah kekurangan? Jatuh cinta mah gak ada yang salah, Siti juga gak pernah, tuh, nyuruh lakinya buat milih dia dan ninggalin istrinya.”
“Kamu suka sama Siti, ya?”
“Apaan sih? Nggak.”
“Kamu belain dia barusan.”
“Hah siapa yang belain, sih? Ya namanya cinta? Mana bisa diajarin?”
Tio ada benarnya.
Eh, iya. Siapa tahu sejak awal kalian penasaran, Tio namanya. Dia temannya Siti, kami berkenalan di suatu malam ketika Siti mengajakku ke Blok M. Tio sebenarnya cukup gila. Tanpa basa-basi, dia langsung meminta nomor teleponku waktu itu. Anehnya, meski perasaanku padanya biasa saja, aku tetap tersenyum ketika sekarang mengingatnya.
“Gue Tio, lo Alina, ya?”
Kalau dipikir-pikir, bukan berkenalan sih, karena dia udah tahu aku duluan. Pasti dari Siti. Dasar bawel.

“Iya, gue Alina,” jawabku sambil menjabat tangannya. Formal ya masih pakai salaman segala, tapi ya udahlah.
“Boleh minta nomor handphone, gak?”
“Boleh, buat apa?”
“Buat ngobrol lagi,”
“Lagi? Kan belum ngobrol daritadi?”
“Oh iya ya? Daritadi kan gue cuma lihatin lo ngobrol aja sama Siti, ya? Abis gak tau kenapa… kayak ikut ngobrol juga rasanya.”
Aku tertawa kecil, mengundang keheranannya, “Kok ketawa?” tanyanya.
“Kata Siti, lo itu orangnya menyenangkan, tapi gue gak tahu kalau menyenangkan yang dia bicarakan itu ternyata maksudnya gombal,” jawabku.
Dia memberiku senyum. “Jadi lo pikir barusan gue gombal? Itu gue kasih informasi, lagi.”
Mungkin sebenarnya Tio tidak pernah berubah, aku saja yang kian hari menyadari bahwa semakin mengenalnya, ternyata semakin menjauhkanku darinya. Mungkin seharusnya, beberapa hal tidak perlu terjadi. Mungkin seharusnya, malam itu aku tidak ikut Siti. Tidak, tidak. Harusnya, aku tidak perlu memberikan Tio nomor teleponku. Harusnya, aku cukup mengetahui sosoknya yang menyenangkan dan cukup tampan itu. Iya. Aku suka senyum kecilnya yang menampakkan sedikit giginya yang rapi. Aku suka aroma tubuhnya sekalipun ia sedang tidak pakai parfum sekali. Ah, ternyata aneh banget ya rasanya? Menceritakan seseorang yang sudah menjadi masa lalu? Kenangan indah memang membuat yang sudah seperti tidak pernah selesai.
“Alina,” panggilnya lagi setelah menyimpan nomor teleponku. “Dibales ya nanti chat gue?”
Sebenarnya aku ingin memberinya jawaban refleks seperti “Tergantung lo chat gue apa” atau “Iya kalau menarik” atau juga “Gak janji sih”, tapi tidak, aku cuma mengangguk dan dia akhirnya pulang dengan motornya. Tidak lama, Siti keluar dan menghampiriku.
“Gimana? Udah kenalan sama Tio?” tanyanya bersemangat.
“Udah gak usah aneh-aneh, deh, Ti. Lo kan tahu gue lagi gak pengin deket ama cowok,”
“Tahu, gue. Lagian lo gak harus deket ama dia, kok, orang dia juga cuma minta nomor handphone, kan? Apa salahnya coba?”
“Mulai deh belaga bego. Lo pasti juga tahu ini arahnya ke mana,”
Ke sebuah tempat. Bukan. Bukan rumah. Meski menurutku sudah tidak ada lagi istilah rumah di muka bumi, tapi kalaupun masih ada, Tio tetap bukan rumah. Dia mungkin rumah bagi dirinya sendiri, makanya, tadinya kupikir, setidaknya hubungan kami akan jauh lebih sederhana, karena bila aku menyakitinya (dan benar aku menyakitinya), ia tetap bisa pulang meski dengan perasaan sedih dan kecewa. Sedangkan Tio jelas tidak boleh menyakitiku, karena aku tidak punya rumah. Aku tidak bisa pulang. Aku cuma bisa sedih dan kecewa.
Tapi yang terjadi justru berbeda. Aku tetap tidak bisa pulang, dan tidak bisa merasakan apa-apa. Aku cuma bisa pergi, tanpa tahu istilah yang tepat untuk menjelaskan langkah kakiku yang berjalan sendiri. Di tengah-tengah obrolanku dengan Siti, handphone-ku berbunyi. Ada pesan masuk dari nomor baru yang belum kusimpan: Ini Tio yang tadi. Jangan dibaca aja. Dibales, ya?
Siti ikut menilik, lalu mengamatiku dengan curiga. “Jangan cuma dibaca aja, dibales…” ejek Siti kepadaku.
Aku menjawab: Iya. Ini dibales.
Tidak sampai lima menit, handphone-ku berbunyi lagi. Dia lagi: Udah disimpen belum nomornya?
Aku menjawab singkat: Udah, Yo.
“Udah mau pulang belum?” tanyanya menghentikan semua lamunanku yang ada di kepala, “Kalau belum, cari makan aja yuk?”
“Cari makan? Yo? Ini udah lewat pukul 2 pagi…”
“Iya… dan aku laper, Alina sayang…” jawabnya sambil menggodaku.
Aku menangkat alis, “Sayang? Sejak kapan ada panggilan itu?”
Dia lalu duduk mendekatiku, tersenyum kemudian memegang wajahku dengan kedua tangannya yang besar. “Sejak hari ini, ya? Boleh ya, Alina? Jangan pake ngomel, ya?”
Aku mematung. Sentuhan tangan selalu menjadi penyebab jantung manusia bisa berdetak lebih kencang. Aku mungkin tidak terlalu mencintainya atau mungkin… aku lumayan mencintainya, itu sebabnya aku tetap gugup ditatapnya seperti itu.

Eh. Jangan larut dulu, ingat itu semua sudah berlalu, itu tidak lebih dari sebuah ingatan setahun yang lalu saat ia masih denganku.
… bersambung
Leave a comment